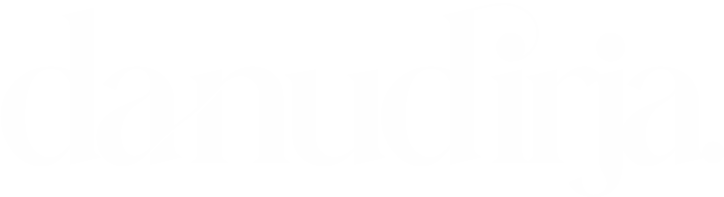Ketika Papua Dirangkum dalam Gambar Laut Jernih dan Burung Cenderawasih
Beberapa waktu terakhir, tagar #SaveRajaAmpat ramai di media sosial. Isunya mengemuka setelah Greenpeace Indonesia mengunggah laporan terkait aktivitas penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Dengan cepat, narasi penyelamatan “surga terakhir di Bumi” mendapat dukungan luas dari publik. Kampanye ini tampak seperti bentuk solidaritas ekologis terhadap Papua.
Namun, seiring mengalirnya pujian, saya merasa ada sesuatu yang mengganjal.
Tagar #SaveRajaAmpat memang menyuarakan kekhawatiran atas kerusakan lingkungan, tetapi sayangnya, ia juga mengaburkan akar persoalan yang jauh lebih dalam, yakni relasi timpang antara negara dan rakyat Papua, serta sejarah panjang eksploitasi dan marginalisasi yang tak pernah selesai.
Papua sering kali hanya tampak ketika ada yang bisa dijual dari tubuhnya, entah itu keindahan alam, kekayaan tambang, atau eksotisme budaya. Isu yang lebih mendasar seperti kekerasan negara, diskriminasi rasial, dan ketimpangan pembangunan cenderung tenggelam. Dan #SaveRajaAmpat, dalam semua kemasan visualnya yang menarik, nyaris tak menyentuh bagian-bagian penting dari narasi besar itu.
Mari kita bandingkan dengan tagar #PapuanLivesMatter dan #AllEyesOnPapua, yang muncul beberapa tahun lalu. Kedua tagar ini membawa konteks yang kuat, tentang nyawa orang Papua yang sering tak dihitung, tentang rasisme struktural yang begitu sistemik. Mereka tidak muncul dalam ruang hampa, tapi sebagai respons terhadap penindasan dan kekerasan nyata yang menimpa warga Papua.
Sebaliknya, #SaveRajaAmpat lahir dari konteks yang lebih steril. Ia terasa aman, enak dikonsumsi, dan indah dibagikan. Siapa yang tak tersentuh melihat video laut biru, terumbu karang, dan burung Cenderawasih disertai musik lembut dan narasi penyelamatan lingkungan? Tapi justru di situlah masalahnya: Papua sekali lagi direduksi menjadi lanskap.
Mengapa tagar yang viral adalah “save Raja Ampat”, dan bukan “save Papua”? Jawabannya mungkin sederhana: Raja Ampat lebih menjual. Raja Ampat lebih mudah disukai. Raja Ampat tidak mengusik rasa bersalah kita. Dalam istilah teori wacana, ini adalah proses dominasi makna: ketika makna tentang Papua ditentukan oleh kepentingan tertentu, dan makna-makna lain, yang lebih kritis dan politis, diabaikan.
Menurut Michel Foucault, realitas bukan sesuatu yang hadir begitu saja, melainkan dibentuk oleh praktik diskursif. Dalam konteks ini, cara kita berbicara tentang Raja Ampat, melalui tagar, kampanye, dan media sosia, sebenarnya adalah cara kita membentuk cara pandang terhadap Papua. Dan ketika satu narasi (lingkungan) mendominasi dan mengesampingkan narasi lain (politik, sejarah, kemanusiaan), maka yang terjadi adalah penyempitan pemahaman publik.
Greenpeace, dengan segala niat baiknya, akhirnya terjebak dalam jebakan itu juga. Mereka tampil sebagai “penyelamat”, mengusung narasi besar tentang penyelamatan bumi, dan setelah izin tambang dicabut, mereka merayakannya dengan slogan: “Kita Menang.”
Tapi siapa “kita” dalam frasa itu? Apakah “kita” juga mencakup masyarakat adat Papua yang hidup di sekitar lokasi tambang? Apakah “kita” mencakup anak muda Papua yang selama ini merasa dimarjinalkan? Ataukah yang dimaksud adalah kelas menengah perkotaan yang selama ini menikmati Raja Ampat sebagai tempat wisata eksklusif?
Jangan-jangan, yang sebenarnya “menang” adalah para pemilik penginapan, operator tur, dan influencer yang menjual narasi Raja Ampat sebagai destinasi bulan madu. Jangan-jangan, yang “menang” adalah mereka yang bisa terbang ke Papua dengan kamera drone, tetapi kembali tanpa sempat berbincang dengan pace dan mace yang tinggal di balik bukit.
Narasi penyelamatan lingkungan yang tak menyentuh dimensi sosial dan politik hanyalah kosmetik. Ia mempercantik permukaan, tetapi membiarkan luka lama tetap menganga. Penambangan nikel di Raja Ampat bukan sekadar persoalan ekologis. Ia adalah gejala dari sistem kekuasaan yang lebih besar, sistem yang sejak lama menjadikan Papua sebagai objek eksploitasi.
Masalah Raja Ampat hari ini tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang seperti New York Agreement, Pepera 1969, kehadiran PT Freeport, hingga pemberlakuan Otonomi Khusus yang menuai protes luas. Bahkan proyek food estate di Merauke pun punya akar yang sama: melihat Papua sebagai ruang kosong yang siap diisi oleh kepentingan negara dan investor.
Ironisnya, banyak dari kita merasa sudah cukup peduli hanya dengan membagikan tagar. Kita lupa bahwa di balik laut jernih Raja Ampat, ada luka panjang yang belum sembuh. Kita lupa bahwa wajah-wajah Papua jarang muncul dalam narasi-narasi viral, kecuali sebagai latar belakang keindahan.
Papua bukan taman nasional. Ia bukan katalog wisata. Ia adalah rumah dari jutaan manusia yang punya sejarah, kehendak, dan suara. Maka, jika kita benar-benar peduli pada Papua, jangan cukupkan diri pada tagar. Gali lebih dalam. Pertanyakan narasi-narasi dominan. Dan jangan segan untuk berdiri di pihak yang tak terdengar.