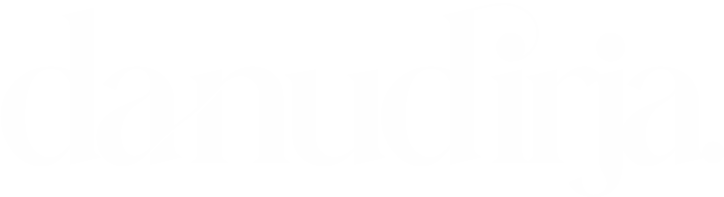Kolaka Utara: Sebuah Epitaf Pembangunan?
Ketika Kapital Melindas Kedaulatan Agraris dan Martabat Rakyat
Di persimpangan janji “kemajuan” dan realitas penderitaan, Kolaka Utara menjadi cermin buram dari sebuah proyek pembangunan yang pincang. Narasi besar tentang pertumbuhan ekonomi seringkali mengaburkan jeritan-jeritan kecil di pedalaman, di mana tanah yang subur dan udara yang bersih kini berganti rupa menjadi lanskap yang tercabik oleh kerakusan kapital. Pilihan antara pembangunan agraris yang berakar atau industri tambang yang menggoda bukanlah sekadar keputusan ekonomi, melainkan pertaruhan hidup-mati bagi rakyat Kolaka Utara yang terpinggirkan.
Ekologi yang Terancam: Membaca Ulang Kontribusi Pertanian
Pemerintah daerah dan para ekonom kerap membanggakan angka: sektor pertanian menyumbang sekitar 40% perekonomian Kolaka Utara. Sebuah fakta yang jelas menunjukkan bahwa pertanian adalah nadi kehidupan, penopang fundamental bagi sebagian besar rakyat. Kakao, kelapa, cengkeh, padi, ikan – ini bukan sekadar komoditas, melainkan wujud kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi lokal yang telah bergenerasi dipegang teguh.
Namun, di balik angka itu, paradigma kritis melihat lebih jauh. Sektor pertanian, yang seharusnya menjadi benteng terakhir kemandirian, justru terus dihadapkan pada ancaman. Pembangunan agraris yang idealnya menciptakan kesejahteraan yang merata, kini harus bergulat dengan ancaman infiltrasi kapital tambang. Pertanian adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, berarti keuntungan yang dihasilkan cenderung didistribusikan lebih luas di antara masyarakat. Ia membangun ikatan komunal dan keberlanjutan ekologis melalui praktik-praktik yang menjaga tanah dan air. Kebijakan pemerintah daerah, seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, patut diapresiasi sebagai upaya defensif. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan sebagai sumber pangan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak. Namun, apakah regulasi ini cukup kuat untuk membendung gelombang investasi tambang yang jauh lebih besar dan kuat? Pertanyaan ini menggantung.
Derasnya Arus Kapital Tambang: Sejarah Penjajahan Modern
Jika pertanian adalah nadi, maka tambang nikel adalah godaan yang perlahan meracuni tubuh Kolaka Utara. Dengan cadangan ore nikel sebesar 2,76 miliar metrik ton dan volume penjualan 500 juta metrik ton, Potensi cadangan nikel yang melimpah menarik investasi besar, menjanjikan pertumbuhan PDB yang fantastis. Namun, bagi kaum kritis, ini adalah narasi usang tentang penjajahan modern yang akan memperdalam ketimpangan. Data menunjukkan bahwa “tingkat pengembalian ke masyarakat sangat rendah karena yang meningkat adalah pengusaha besar, pemilik modal” adalah pengakuan telanjang akan ketidakadilan struktural. Keuntungan tambang, alih-alih mensejahterakan rakyat, justru terakumulasi di tangan segelintir elite dan korporasi transnasional, menyisakan remah-remah bagi masyarakat lokal.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kolaka Utara bersama Gerakan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kolaka Utara pada 21 Mei 2025, Haeruddin, selaku koordinator aksi, menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya alam belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sudah puluhan tahun tambang berjalan, tapi rakyat hanya dapat remah. Dana Bagi Hasil yang diterima sangat kecil dan tidak mampu menopang pembangunan daerah,” tegasnya.
Data bps menunjukkan, setidaknya 23 perusahaan nikel beroperasi di Kolaka Utara, dari total 24 perusahaan pertambangan yang memiliki akses beroperasi. Beberapa di antaranya yang aktif atau memiliki kuota RKAB per Februari 2025 antara lain PT Putra Dermawan Pratama (PDP), PT Kasmar Tiar Raya (KTR), PT Fatwa Bumi Sejahtera, PT Patrindo Jaya Makmur, PT Citra Silika Mallawa (CSM), PT Riota Jaya Lestari, PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMIN), PT Kurnia Mining Resource (KMR), PT Mulia Makmur Perkasa, PT Tambang Mineral Maju (TMM), dan PT Shenniu Mining Indonesia. Keberadaan puluhan perusahaan ini memperparah ancaman terhadap lingkungan dan masyarakat.
Dampak buruk tambang bukanlah efek samping, melainkan konsekuensi logis dari model eksploitasi yang rakus
Perampasan Sumber Daya Pencemaran air oleh lumpur dan logam berat, polusi udara yang mencekik dengan debu nikel, dan kerusakan lahan yang permanen bukan sekadar “dampak,” melainkan perampasan hak dasar atas lingkungan hidup yang sehat. Berbagai laporan berita mengindikasikan bahwa masyarakat di beberapa desa, seperti Desa Muara Lapapao, Desa Lelewawo, Mosiku, dan Tetebo, mengalami pencemaran air laut dan sungai. Sumur warga rusak dan kekeruhan air membuat ikan enggan mendekati pesisir. Tanaman sagu, yang merupakan sumber penghidupan, banyak yang mati akibat lumpur tebal limbah tambang. Bahkan, ada laporan tiga kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terancam longsor bekas tambang. Mereka yang seharusnya menjadi pewaris tanah, kini menjadi penyintas limbah dan polusi.

Fragmentasi Sosial: Komunitas yang dulunya kohesif kini terbelah oleh janji-janji palsu pekerjaan atau konflik lahan. Keberadaan tambang memang memicu pertumbuhan usaha seperti rumah kos-kosan dan rumah makan, serta membuat beberapa warga “banting setir” mencari pekerjaan baru di sektor yang terkait dengan tambang. Namun, dampak sosialnya tidak selalu positif. Aktivitas gotong royong dilaporkan berkurang di beberapa desa. Pembangunan smelter, yang digadang-gadang sebagai hilirisasi, seringkali hanya menggeser masalah lingkungan dan eksploitasi ke tahapan yang lebih kompleks, tanpa distribusi manfaat yang berarti bagi masyarakat lokal.

Ketergantungan yang Rentan: Menggantungkan masa depan pada sumber daya tak terbarukan adalah resep menuju kehancuran jangka panjang. Ketika nikel habis, Kolaka Utara akan ditinggalkan dengan lubang menganga, tanah tandus, dan masyarakat yang kehilangan keterampilan agrarisnya. Ini adalah pembangunan yang tidak berkelanjutan, yang menukar masa depan dengan keuntungan sesaat.
Kebijakan Pemerintah Daerah: Sebuah Dilema Struktural?
Kebijakan pemerintah daerah Kolaka Utara menunjukkan dilema klasik di negara-negara berkembang. Di satu sisi, ada pengakuan terhadap pentingnya pertanian dan upaya defensif seperti PERDA Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pejabat daerah juga sering menegaskan prioritas pada sektor agraris sebagai penopang ekonomi daerah. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan identitas agraris Kolaka Utara.
Namun, di sisi lain, potensi tambang tetap menjadi magnet yang kuat. Masuknya tambang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan dorongan dari sebagian fraksi DPRD untuk mengoptimalkan potensi ini, bahkan melalui BUMD, mengindikasikan adanya tekanan kapital dan kepentingan elite yang sulit dihindari. Pertanyaan kritisnya adalah: apakah pemerintah daerah memiliki kapasitas dan kemandirian politik yang cukup untuk mengontrol raksasa tambang, ataukah mereka justru terjebak dalam logika pertumbuhan ekonomi yang didikte oleh investasi besar? Apakah janji optimalisasi PAD benar-benar akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, ataukah hanya akan memperkuat segelintir oligarki lokal?
Epilog: Memutus Rantai Eksploitasi
Kolaka Utara berdiri di ambang jurang. Pilihan arah pembangunan bukanlah sekadar soal angka PDB, melainkan soal keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keberlanjutan ekologis. Paradigma kritis menuntut kita untuk tidak hanya melihat potensi, tetapi juga struktur eksploitasi yang melekat pada model pembangunan berbasis tambang.
Masa depan Kolaka Utara tidak terletak pada penyerahan diri pada godaan modal tambang yang destruktif, melainkan pada penguatan kedaulatan agraris rakyat. Ini berarti:
Revitalisasi Sejati Pertanian: Bukan hanya di atas kertas, tetapi dengan investasi nyata, perlindungan hukum yang kuat, dan pemberdayaan petani agar menjadi aktor utama, bukan objek pembangunan. Ini mencakup penerapan Perda No. 3 Tahun 2023 secara konsisten dan tegas, memastikan lahan pertanian terlindungi dari ekspansi tambang.
Tolak Tambang Destruktif: Jika pertambangan tetap dilakukan, harus dengan prinsip non-negosiasi terhadap kerusakan lingkungan dan pengabaian hak rakyat. Audit menyeluruh terhadap puluhan perusahaan tambang nikel yang beroperasi, penegakan hukum yang tak pandang bulu terhadap pelanggaran lingkungan dan korupsi, serta mekanisme ganti rugi yang adil bagi masyarakat terdampak adalah mutlak, bukan pilihan. Kasus-kasus pencemaran dan pengungsian warga harus ditangani serius dan tuntas.
Demokratisasi Ekonomi: Membangun struktur ekonomi yang memungkinkan manfaat didistribusikan secara adil, bukan terakumulasi di puncak piramida. Ini berarti meninjau ulang regulasi dan kebijakan yang menguntungkan korporasi besar dan menciptakan celah bagi praktik-praktik ilegal, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap keputusan pembangunan.
Kolaka Utara bukanlah sekadar lahan konsesi, melainkan rumah bagi ribuan jiwa yang berhak atas kehidupan yang layak dan bermartabat. Sudah saatnya kita tidak hanya berbicara tentang “pembangunan,” tetapi tentang pembebasan dari cengkeraman sistem yang mengorbankan rakyat dan bumi demi keuntungan segelintir pihak. Bisakah Kolaka Utara menuliskan kisah kemenangan agraris, ataukah ia akan menjadi epitaf suram dari sebuah pembangunan yang mengkhianati rakyatnya sendiri?