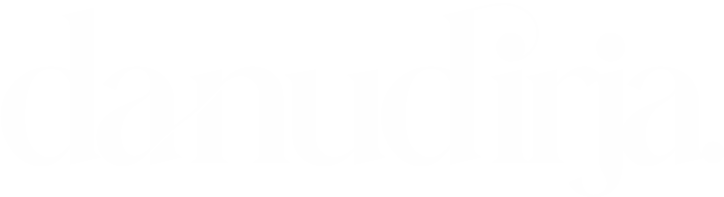Mengapa Negara Takut Terhadap Simbol-Simbol Seni?
Awal Agustus yang lalu, negara kembali merasa terancam dengan maraknya pengibaran bendera One Piece Jolly Roger. Fenomena ini mendapat respons dari pemerintah yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap nasionalisme bahkan bisa memecah belah bangsa sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. “Kami mendeteksi dan mendapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan memang ada upaya memecah belah persatuan dan kesatuan,” Kamis, 31 Juli 2025.
Bukan hanya Dasco, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan juga menyoroti kasus pengibaran bendera One Piece yang menggantikan bendera Merah Putih. Budi menyebut aksi ini sebagai provokasi dari kelompok tertentu yang tidak menghargai nilai sejarah bangsa. Budi Gunawan mengingatkan bahwa bendera Merah Putih adalah simbol hasil perjuangan bersama para pahlawan. Ia meminta masyarakat tidak memprovokasi dengan menggunakan simbol-simbol yang tidak ada kaitannya dengan perjuangan bangsa. Ia juga mengingatkan bahwa tindakan merendahkan kehormatan bendera negara bisa dikenai sanksi pidana, sesuai undang-undang yang melarang pengibaran bendera negara di bawah bendera atau lambang apapun. Terakhir Ia menegaskan, akan mengambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional jika ada unsur kesengajaan dan provokasi, untuk menjaga ketertiban dan kewibawaan simbol negara.
Fenomena ini bukan yang pertama. Sepanjang sejarah, bisa dilihat bagaimana negara bereaksi keras terhadap berbagai bentuk ekspresi seni, seperti mural jalanan, lagu-lagu protes, hingga pertunjukan teater yang dianggap subversif.
Lalu mengapa negara dengan segala kekuatan militer dan ekonominya begitu takut terhadap simbol-simbol seni? Pertanyaan inilah yang akan saya uraikan pada tulisan ini.
Seni Menjadi Medan Perang
Melihat fenomena ini, Antonio Gramsci, pemikir Marxis Italia, memberikan perspektif melalui konsep hegemonimya. Menurut Gramsci, kekuasaan sejati tidak hanya ditegakkan melalui kekerasan fisik tetapi juga melalui dominasi budaya dan ideologis. Negara tidak cukup hanya menguasai tentara dan polisi, ia harus menguasai pikiran dan jiwa rakyatnya. Di sinilah seni dan simbol-simbol budaya menjadi medan pertempuran yang sesungguhnya.
Gramsci membedakan antara political society (masyarakat politik) dan civil society (masyarakat sipil). Political society beroperasi melalui kekerasan dan paksaan, sementara civil society beroperasi melalui konsensus dan persuasi. Seni, budaya, pendidikan, dan media massa adalah bagian dari civil society yang menjadi arena kontestasi hegemonik.
Dalam konteks Indonesia, fenomena pengibaran bendera One Piece Jolly Roger menunjukkan bagaimana simbol-simbol seni dapat menjadi medium untuk mengekspresikan aspirasi politik alternatif. Ketika masyarakat mengadopsi simbol bajak laut yang melawan pemerintah dunia yang korup dalam cerita anime one piece, mereka secara tidak langsung sedang mengkritik kondisi politik di sekitar mereka.
Seni Sebagai “Organic Intellectual” dalam Masyarakat
Konsep lain dari Gramsci adalah organic intellectual, yaitu individu atau kelompok yang muncul dari kelas tertentu dan berperan sebagai pemikir serta organisator kesadaran kelas tersebut. Seniman, dalam konteks ini, sering berperan sebagai organic intellectual yang mampu mengartikulasikan aspirasi dan kritik masyarakat dalam bentuk yang mudah dipahami dan dirasakan.
Penelitian terbaru tentang seni jalanan di Asia Tenggara menunjukkan bagaimana mural, graffiti, dan bentuk-bentuk seni publik lainnya berfungsi sebagai medium untuk mengkritik ketimpangan sosial, korupsi, dan autoritarianisme. Seniman jalanan berperan sebagai organic intellectual yang menggunakan ruang publik sebagai canvas untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat. Begitu pula dengan musik, lagu-lagu protes seperti “Bella Ciao” yang diadopsi oleh berbagai gerakan sosial di dunia, atau lagu-lagu punk rock Indonesia yang mengkritik sistem, berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesadaran kritis. Musik memiliki kekuatan emosional yang dapat memobilisasi massa dan menciptakan solidaritas diantara pendengarnya (Reed, 2019).
War of Position: Strategi Perjuangan Melalui Budaya
Gramsci juga memperkenalkan konsep war of position (perang posisi) sebagai lawan dari war of maneuver (perang gerak). Jika war of maneuver adalah konfrontasi langsung seperti revolusi bersenjata, maka war of position adalah perjuangan jangka panjang untuk menguasai institusi-institusi civil society, seperti sekolah, media, organisasi budaya, dan ruang-ruang produksi makna lainnya.
Dalam war of position ini, seni berperan sebagai senjata yang sangat efektif. Karya seni memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan ideologis yang dibangun oleh kelas berkuasa. Sebuah lagu, lukisan, atau bahkan meme internet dapat menyampaikan kritik politik yang lebih tajam daripada artikel opini atau pidato politik formal.
Fenomena pengibaran bendera One Piece Jolly Roger adalah contoh dari war of position. Tanpa perlu melakukan demonstrasi atau aksi politik langsung, masyarakat menggunakan simbol seni untuk mengekspresikan kerinduan mereka akan kebebasan dan keadilan. Simbolisme bajak laut yang melawan sistem yang korup menjadi metafora yang kuat untuk kondisi politik saat ini (Daliot-Bul & Otmazgin, 2017).
Era Digital dan Transformasi Ruang Seni
Tahun 2022 saya pernah menyampaikan bahwa media sosial bisa menjadi alternatif perjuangan dalam melawan status quo. Hal ini saya tuangkan dalam tesis saya yang berjudul, Kritik Mahasiswa Terhadap Kebijakan Jokowi: Analisis Wacana Gerakan kritik Mahasiswa Di Media Sosial Instagram Tahun 2021.
Media sosial telah mentransformasi cara seni diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter memungkinkan seniman untuk langsung terhubung dengan audiensnya tanpa melalui gatekeeper tradisional seperti galeri, label rekaman, atau penerbit. Demokratisasi ini membuat negara kesulitan mengontrol produksi dan sirkulasi karya seni.
Studi tentang aktivisme digital menunjukkan bagaimana meme, video viral, dan konten-konten kreatif lainnya telah menjadi bentuk baru dari resistensi budaya. Di era digital dan media sosial seperti sekarang, seni visual seperti ilustrasi, poster, atau meme menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan kesadaran dan menggerakkan orang agar peduli pada isu-isu sosial. Meski begitu, seni juga rentan terhadap komersialisasi yang dapat mengaburkan pesan awalnya, atau bahkan diubah maknanya oleh kepentingan tertentu.
Ketika pengibaran bendera One Piece Jolly Roger itu viral, itu menunjukkan bagaimana simbol seni dapat menciptakan gerakan budaya yang melampaui batas geografis dan demografis. Negara kesulitan menghadapi fenomena ini karena sifat internet yang partisipatif. Berbeda dengan media massa tradisional yang terpusat dan mudah dikontrol, media sosial memungkinkan siapa saja untuk menjadi produser konten. Ketika sebuah karya seni atau simbol budaya menjadi viral, negara cukup sulit untuk mengendalikan narasinya.
Mengapa Negara Begitu Takut?
Ternyata, kekhawatiran negara terhadap simbol-simbol seni justru menunjukkan betapa kuatnya pengaruh seni itu sendiri. Seni punya kemampuan luar biasa untuk membentuk identitas bersama. Misalnya, ketika masyarakat mengibarkan bendera One Piece, itu bukan sekadar suka pada sebuah anime, tetapi juga membangun rasa kebersamaan atas nilai-nilai seperti kebebasan, persahabatan, dan melawan ketidakadilan.
Selain itu, seni bisa menyatukan orang dari berbagai latar belakang. Berbeda dengan politik yang sering terasa elitis, seni bisa dinikmati bagi semua kelas-kelas sosial, terkecuali bagi pemerintah saat ini. Bagi saya melarang dan hawatir terhadap fenomena ini adalah sebagai bentuk ketidakmampuan untuk menikmati seni itu sendiri.
Seni juga mampu membangkitkan emosi yang bisa menggerakkan banyak orang. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sri Zuliari (2017) yang menegaskan bahwa ekspresi simbolis melalui seni menjadi alat utama perjuangan untuk membela kepentingan rakyat. Karya seni bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga alat kritik dan kontrol sosial yang mampu membangkitkan emosi kolektif serta menjadi sarana pendidikan politik masyarakat. Seni dalam konteks ini berfungsi sebagai perekat solidaritas dan penggerak perlawanan.
Strategi Negara dalam Menghadapi Ancaman Seni
Ketika menghadapi simbol-simbol seni yang dianggap berbahaya, negara biasanya punya dua cara untuk merespons. Cara pertama adalah dengan paksaan, seperti melarang karya seni, menyensor, atau bahkan menangkap senimannya. Namun, cara ini sering kali berbalik merugikan bagi negara, karya yang dilarang justru makin terkenal dan senimannya bisa dilihat sebagai korban. Cara ini bisa dilihat dari penutupan pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto, yang berjudul “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan” tahun 2024.
Cara kedua lebih halus, yaitu dengan membujuk dan mengambil alih. Misalnya, negara bisa mengajak seniman untuk bekerja sama, membuat karya seni sendiri yang mendukung pemerintah, atau mengubah makna simbol perlawanan menjadi sesuatu yang tidak berbahaya. Sebagaimana dalam penelitian Budiman (2024), bahwa pemerintah melalui KCCI melibatkan seniman, influencer, dan komunitas kreatif untuk memperluas pengaruh budaya, bukan dengan pemaksaan melainkan dengan kolaborasi dan proyek bersama. Strategi ini memperlihatkan bagaimana kekuatan persuasif lebih efektif dalam membangun penerimaan, apresiasi, dan perubahan makna simbol budaya di masyarakat.
Menurut saya, daripada melarang, sebenarnya negara bisa saja memilih untuk tidak bereaksi sama sekali terhadap fenomena pengibaran bendera One Piece Jolly Roger. Di Indonesia, tren yang viral biasanya cepat hilang jika tidak dapat perhatian. Justru ketika pemerintah bereaksi berlebihan atau melarang, masyarakat menjadi penasaran dan ingin tahu lebih jauh. Hal ini membuat fenomena tersebut makin terkenal dan bertahan lebih lama. Jadi, dengan tidak memberi respons, makna dan dampak simbol itu bisa melemah dengan sendirinya.
Cara negara menanggapi simbol-simbol seni, sebenarnya bisa menjadi cerminan seberapa sehat demokrasi kita. Di negara yang benar-benar demokratis, keberagaman ekspresi seni justru dihargai sebagai tanda bahwa masyarakatnya hidup dan kreatif, bukan dianggap sebagai ancaman. Jika pemerintah bereaksi berlebihan terhadap hal-hal seperti ini, itu malah menunjukkan bahwa kekuasaan mereka sebenarnya rapuh dan hanya bertahan karena dipaksakan.
Negara yang benar-benar kuat tidak akan merasa terancam oleh simbol-simbol seni ini. Justru, dengan membiarkan orang berkreasi dan berekspresi, pemerintah menunjukkan bahwa mereka menghormati kebebasan warganya. Sebaliknya, jika setiap simbol kecil langsung dilarang atau ditindak tegas, itu justru bisa memicu rasa penasaran dan perlawanan yang lebih besar.
Pada dasarnya, rasa takut negara terhadap simbol-simbol seni justru menunjukkan kelemahan tersembunyi dari kekuasaan itu sendiri. Di satu sisi, negara punya kekuatan untuk mengontrol banyak hal. Tapi di sisi lain, kekuasaan itu sebenarnya bergantung pada pengakuan dan dukungan dari rakyat yang bisa saja goyah hanya karena sebuah bendera kartun fiksi.
Kekuasaan yang sejati bukanlah tentang memaksa, tapi tentang meyakinkan. Ketika negara lebih memilih melarang dan menekan daripada berdialog, itu pertanda bahwa kepercayaan masyarakat mulai menipis. Bagi saya, situasi ini justru membuka peluang untuk menyebarkan gagasan lewat karya seni, simbol, atau konten kreatif, cara yang lebih aman dan berkelanjutan untuk mendorong perubahan sosial daripada melawan secara langsung.
Menurut saya, fenomena seperti pengibaran bendera One Piece Jolly Roger, mengingatkan bahwa seni bukan sekadar hiburan. Itu adalah cara menyampaikan suara, kritik, dan harapan. Di era digital seperti sekarang ini, siapa pun bisa ikut membentuk opini melalui konten yang dibuat, karen itu menjadi bagian dari perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan demokratis.