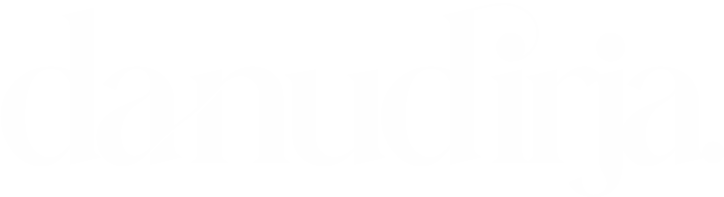Sebelum memasuki pembahasan utama, perlu disampaikan bahwa menerjemahkan istilah “camp” ke dalam bahasa Indonesia cukup sulit. Sebagian besar orang di Indonesia memahami kata “kamp” dalam pengertian yang sangat berbeda, seperti kegiatan berkemah (camping) yang bersifat rekreasional. Selain itu, dalam bahasa Indonesia sendiri, kata “kamp” juga sering dikaitkan dengan penjara atau tempat tahanan, yang membawa konotasi pembatasan kebebasan dan pengucilan. Ambiguitas makna ini kerap menyulitkan penulis untuk menyampaikan konsep “kamp” dalam konteks akademis dan sosial-politik secara tepat, mengingat istilah tersebut meliputi berbagai jenis institusi yang jauh lebih kompleks, seperti kamp pengungsi, kamp penahanan, dan kamp re-edukasi. Oleh karena itu, penjelasan kontekstual menjadi penting agar pembaca dapat memahami makna istilah “kamp” sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam tulisan ini.
Realitas Tersembunyi di Balik Institusi Kamp
Di abad ke-21, kehidupan jutaan orang ternyata masih berlangsung di dalam berbagai bentuk “kamp”. Bukan cuma kamp pengungsian di perbatasan daerah perang, tetapi juga kamp penahanan imigran di negara maju atau kamp “pendidikan ulang” kontroversial di beberapa negara. Keberadaan kamp-kamp ini bukanlah peninggalan sejarah semata, melainkan realitas zaman sekarang yang terus berubah mengikuti perkembangan politik global.
Penelitian terbaru oleh Bochmann dan Purdeková (2025) mengungkap fakta mengejutkan: kamp kini telah menjadi alat pengelolaan masyarakat yang dianggap “wajar” dan digunakan luas oleh negara demokratis maupun otoriter. Lebih dari itu, temuan ini membongkar pemahaman teori studi kamp selama ini—khususnya teori filsuf Italia Giorgio Agamben—karena kamp bukan lagi pengecualian, melainkan bagian dari sistem pengendalian yang normal.
Agamben dan Teori “Ruang Pengecualian”
Untuk memahami signifikansi temuan Bochmann dan Purdeková, kita perlu terlebih dahulu memahami teori influential Giorgio Agamben tentang kamp. Bayangkan sebuah akuarium raksasa di tengah kota, penghuninya (tahanan) terlihat jelas, tapi tak bisa bersuara. Status mereka cuma “ikan” (bare life). Penjaganya bisa menyetrum ikan itu kapan saja tanpa dihukum, karena akuarium adalah “zona khusus” dan orang di luar jalan saja sambil makan es krim, berpikir: “Ah, kan bukan aku yang di dalam…”. Tanpa disadari, pemerintah mulai bangun akuarium-akuarium baru—lebih kecil dan tersembunyi—di sudut-sudut kota.
Agamben mengonseptualisasikan kamp sebagai “ruang pengecualian” (space of exception) – sebuah zona di mana hukum normal ditangguhkan dan individu direduksi menjadi apa yang ia sebut “kehidupan telanjang” (bare life). Menurut Agamben, kamp adalah manifestasi dari kekuasaan berdaulat yang paling ekstrem, di mana manusia kehilangan status politisnya dan menjadi sekedar kehidupan biologis yang dapat dikorbankan.
Menurut filsuf Giorgio Agamben, kamp bukan sekadar penjara biasa. Ini adalah zona khusus di mana negara sengaja “mematikan” hukum. Bayangkan aturan masyarakat seperti tombol lampu: di luar kamp, tombolnya “ON” (ada polisi, pengadilan, hak warga). Di dalam kamp, tombolnya “OFF”. Tanpa perlindungan hukum, manusia direduksi jadi sekadar “tubuh biologis” atau bare life (kehidupan telanjang): mereka hanya dianggap makhluk yang butuh makan, tidur, dan bekerja—bukan warga negara dengan hak politik. Contoh nyatanya adalah kamp konsentrasi Nazi: di sana, tentara bisa menyiksa atau membunuh tahanan tanpa proses hukum, karena kamp sengaja dibuat sebagai “pulau” di mana konstitusi tidak berlaku.
Agamben meyakini logika kamp tidak terkubur bersama sejarah. Justru, ia menjadi virus tersembunyi dalam politik modern. Prinsip “zona bebas hukum” ini menyebar dalam bentuk baru: – Fisik: Pusat detensi imigran (seperti di perbatasan AS/Meksiko) di mana orang ditahan bertahun-tahun tanpa pengadilan. – Digital: Sistem pengawasan massal (misal: pelacakan wajib lewat CCTV AI) yang mencabut hak privasi tanpa izin pengadilan. – Hukum: Kebijakan darurat (seperti larangan demo dengan alasan “keamanan nasional”) yang membungkam kritik. Di sini, kelompok rentan (imigran, minoritas, aktivis) paling rentan kehilangan status hukumnya. Mereka bisa tiba-tiba berubah dari “warga” jadi “terdakwa” tanpa perlindungan.
Paradigma Agamben ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman kamp konsentrasi Nazi, yang ia anggap sebagai paradigma politik modern par excellence. Dalam pandangan ini, kamp berfungsi sebagai ruang eksklusi di mana norma-norma hukum dan politik biasa tidak berlaku, dan di mana kekuasaan berdaulat dapat beroperasi tanpa batasan. Teori ini telah menjadi sangat influential dalam studi kamp, khususnya dalam analisis kamp pengungsi dan migrasi.
Peringatan terbesar Agamben: mekanisme ini ibarat kanker yang bisa menjalar. Awalnya, negara hanya terapkan ke kelompok “tersangka” (misal: teroris atau imigran ilegal). Tapi lambat laun, alasannya bisa diperlebar: > *\”Dulu Nazi hanya penjarai Yahudi, lalu meluas ke Gipsi, homoseksual, hingga kritikus politik.” Contoh modern: – Pembenaran “Darurat”: Saat pandemi COVID-19, beberapa negara berlakukan lockdown ekstrem tanpa kontrol parlemen. – Erosi Hak Bertahap: Awalnya detensi imigran 7 hari, lalu jadi 1 tahun, lalu tanpa batas waktu. Intinya: Ketika masyarakat diam melihat satu kelompok dicabut haknya, suatu saat mekanisme sama bisa digunakan untuk menarget siapa saja—termasuk kita.
Namun, Agamben juga mengargumentasikan bahwa kamp bukan hanya fenomena historis yang terisolasi, melainkan telah menjadi “paradigma tersembunyi” politik modern. Menurutnya, logika kamp telah menyebar ke berbagai aspek kehidupan politik kontemporer, menciptakan berbagai bentuk “ruang pengecualian” baru di mana kekuasaan berdaulat dapat beroperasi di luar batasan hukum normal.
Menantang Paradigma Dominan: Temuan Empiris yang Revolusioner
Penelitian Bochmann dan Purdeková, yang menganalisis lima jenis kamp berbeda – kamp penjara Guantanamo Bay, kamp penahanan di Xinjiang China, kamp re-edukasi di Rwanda, kamp pengungsi di perbatasan Myanmar-Thailand, dan kamp relokasi pasca-bencana di Filipina dan Jepang – menghadirkan bukti empiris yang menantang paradigma Agamben secara fundamental.
Temuan pertama yang mengejutkan adalah bahwa semua jenis kamp, meskipun tampak sangat berbeda dalam bentuk dan konteksnya, pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial-politik. Berlawanan dengan konsep Agamben tentang kamp sebagai ruang eksklusi, penelitian ini menunjukkan bahwa kamp sebenarnya adalah teknologi inklusi yang dikelola. Kamp menangani populasi yang dianggap “tidak pada tempatnya” – pengungsi, “teroris”, mantan kombatan, atau korban bencana – bukan untuk mengeksklusi mereka secara permanen, melainkan untuk memproses dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam tatanan sosial yang diinginkan.
Temuan kedua yang tidak kalah revolusioner adalah bahwa kamp mengembangkan dinamika governance yang otonom dan tidak sepenuhnya dikontrol oleh penciptanya. Setelah didirikan, kamp berkembang menjadi entitas sosial yang memiliki logika institusional sendiri, di mana berbagai aktor – mulai dari penghuni kamp, petugas, organisasi internasional, hingga masyarakat lokal – terlibat dalam negosiasi kekuasaan yang kompleks. Realitas ini jauh dari gambaran Agamben tentang kamp sebagai ruang di mana kekuasaan berdaulat beroperasi secara absolut.
Governance Multi-Dimensi: Melampaui Kekuasaan Berdaulat
Penelitian di lima kamp mengungkap tiga cara pengelolaan yang dipakai bersamaan:
Pertama, inklusi – berupa program pelatihan atau pendidikan untuk “membentuk ulang” penghuni sesuai nilai penguasa. Kedua, eksklusi – melalui pembatasan fisik seperti pagar tinggi dan larangan komunikasi yang mengisolasi penghuni dari dunia luar. Ketiga, liminalitas – menciptakan status “digantung” (misal: status pengungsi bertahun-tahun tanpa kepastian) agar penghuni mudah dikontrol secara psikologi.
Pasca-genosida, Rwanda membuat kamp “solidaritas” yang berfungsi seperti pabrik rekayasa sosial. Kamp ini menggunakan: Pemisahan fisik (lokasi terpencil di pegunungan), Jadwal hiper-ketat (aktivitas diatur 18 jam/hari untuk menghilangkan otonomi), Simulasi pengalaman (drama paksa tentang persatuan). Tujuannya memaksa penghuni menerima nilai-nilai baru pemerintah.
Di Xinjiang China, kamp penahanan menggabungkan metode lama (seperti pengakuan paksa ala era Mao) dengan teknologi modern (pengenalan wajah AI, drone). Paradoksnya, justru memicu perlawanan kreatif seperti kode rahasia antar-tahanan. Sementara di Guantanamo Bay – meski dikenal dengan penyiksaan dan status hukum “abu-abu” – tahanan mengembangkan strategi perlawanan mulai dari mogok makan hingga menulis puisi tersembunyi.
Kamp adalah alat kontrol melalui ruang dan waktu: pagar bukan sekadar pembatas, tapi simbol kekuasaan; jadwal ketat dirancang menghancurkan kemandirian. Namun sejarah membuktikan: di mana ada penindasan, di situ selalu tumbuh perlawanan – entah secara terbuka atau diam-diam – karena manusia pada dasarnya mencari celah untuk merdeka.
Bayangkan kamp seperti sekolah penjara:
- Bangunannya (pagar, menara pengawas) = alat eksklusi
- Jadwal bell tiap jam = alat liminalitas
- Pelajaran kewarganegaraan = alat inklusi
Tapi murid-muridnya tetap bisa menyelundupkan catatan protes atau bolos lewat lubang pagar.
Sociomateriality dan Dinamika Lokal
Penelitian di kamp pengungsi Thailand-Myanmar menunjukkan bahwa bentuk fisik kamp (seperti desain bangunan, pagar pembatas, dan infrastruktur) bukan sekadar tempat tinggal. Elemen-elemen fisik ini justru menjadi alat kontrol yang membentuk kehidupan sosial penghuni dan sekaligus memperlihatkan cara kerja kekuasaan global. Namun uniknya, warga kamp menciptakan strategi lokal untuk mengakali pembatasan fisik tersebut, sehingga terbentuk tatanan sosial yang berbeda dari rencana pengelola kamp.
Meskipun penghuni berusaha menghindari pembatasan fisik dan isolasi, status mereka sebagai kelompok terpinggirkan tetap terpelihara—justru oleh tata ruang dan material kamp itu sendiri. Hal ini membuktikan dua hal:
- Material kamp sangat dominan dalam mengatur kehidupan sehari-hari;
- Tumbuhnya dinamika lokal mandiri (seperti sistem gotong-royong atau ekonomi informal) yang tidak pernah diantisipasi oleh desain awal kamp.
Implikasi Teoretis dan Praktis
Temuan-temuan empiris ini memiliki implikasi yang mendalam untuk pemahaman teoretis tentang kamp dan governance modern. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa kamp bukan lagi pengecualian tetapi telah menjadi norma yang diharapkan dalam governance kontemporer. Kamp-kamp modern tidak beroperasi di luar hukum, melainkan dalam kerangka hukum yang kompleks yang melibatkan berbagai tingkat governance – dari global hingga lokal.
Kedua, fokus Agamben pada “kehidupan telanjang” dan governance tubuh mengabaikan mode-mode governance yang lebih tidak kasat mata, seperti governance kehilangan dalam kamp relokasi paksa di Filipina. Kamp relokasi ini bukan hanya respons terhadap kehilangan, tetapi justru mendefinisikan dan memproduksi bentuk-bentuk kehilangan melalui konstitusi dan operasi mereka sendiri. Bentuk-bentuk governance ini – yang tidak fokus pada tubuh tetapi pada aspek-aspek kehidupan yang tidak kasat mata – tidak dapat ditangkap dengan baik oleh konsepsi Agamben maupun Foucault tentang kamp.
Ketiga, paradigma eksklusi Agamben sangat bermasalah ketika diterapkan pada kamp re-edukasi, relokasi, dan bentuk-bentuk kamp lainnya yang berada di “dalam negara”. Di sini, paradigma eksklusi sama sekali tidak berlaku, dan kamp justru menjadi ruang inkorporasi yang dipaksakan melalui re-alignment dan remaking warga negara. Bahkan untuk kamp migrasi dan pengungsi, tujuan politik keseluruhan adalah untuk mengatasi eksklusi dan mereintegrasi mereka yang dikampkan ke dalam tatanan sosial-politik yang berlaku melalui resettlement, reintegrasi, atau repatriasi/deportasi.
Kesimpulan: Menuju Pemahaman Baru tentang Kamp
Penelitian Bochmann dan Purdeková menghadirkan argumen yang kuat bahwa kamp bukanlah ruang pengecualian yang mengungkap norma, melainkan telah menjadi norma yang diharapkan dalam governance kontemporer. Kamp bukan ruang eksklusi a priori, tetapi alat untuk bentuk inklusi yang dikelola. Dalam pandangan dasarnya, kamp adalah teknologi kekuasaan yang berorientasi pada pembuatan dan konsolidasi tatanan, di mana segmen-segmen populasi tertentu ditempatkan dan/atau dikerjakan untuk memasukkan mereka kembali ke dalam tatanan sosial dan politik yang berlaku.
Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa grand design tidak selalu menjamin hasil yang diinginkan. Kamp dapat menjadi tempat yang hiperpolitik, panggung untuk pengorganisasian politik, pembentukan partai politik baru di pengasingan, dan ruang mobilisasi militer. Demikian pula, kamp yang ditujukan untuk penahanan dan kontrol maksimum seperti di Guantanamo atau Xinjiang, dengan inovasi teknologi yang terus berkembang, juga dipenuhi dengan politik dan berbagai bentuk perlawanan.
Pada akhirnya, penelitian ini mengungkap bahwa kamp bukan hanya mesin kekuasaan, tetapi institusi sosial yang sangat terpolitisasi. Kompleksitas ini hanya menekankan pentingnya memperhatikan bagaimana logika yang mendorong konstruksi kamp diterjemahkan ke dalam materialitas kontingen di lapangan. Dengan demikian, pemahaman tentang kamp sebagai teknologi kekuasaan modern memerlukan pendekatan yang lebih nuanced dan empiris, yang mampu menangkap dinamika kompleks antara desain kekuasaan dan realitas kehidupan di dalamnya.